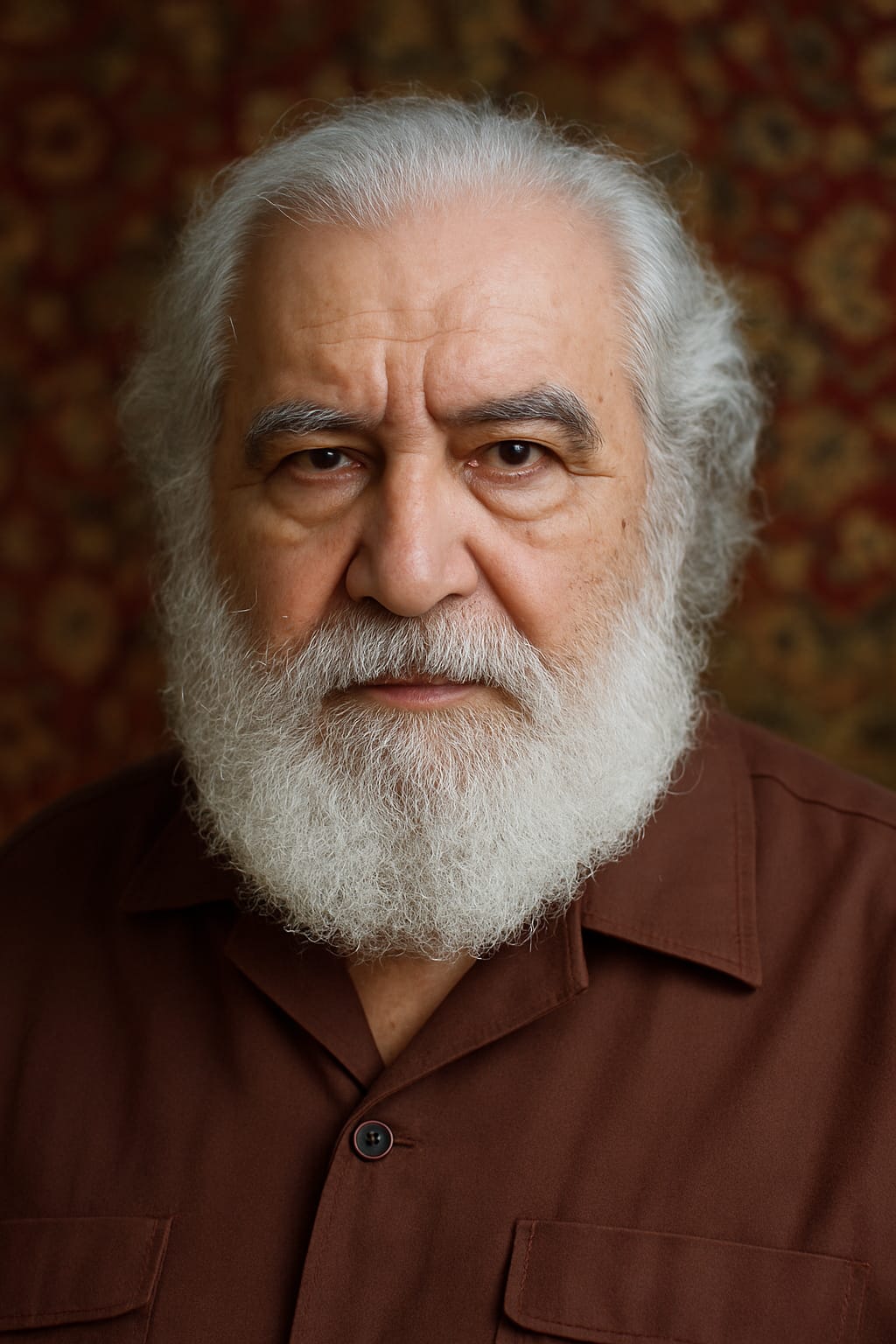Dr. H. Tirtayasa, S.Ag., M.A.
Kader Seribu Ulama Doktor
MUI dan Baznas RI Pusat Angkatan 2021
Di tengah keramaian wacana global tentang krisis makna, “post-truth”, dan kelesuan pendidikan, nama Syed Muhammad Naquib al-Attas hadir bukan sekadar sebagai akademikus, tetapi sebagai perumus kerangka besar—worldview Islam—yang menata kembali hubungan manusia dengan pengetahuan, bahasa, dan adab. Gagasannya menolak godaan penyederhanaan: ia memadukan filologi, teologi, filsafat, dan sejarah peradaban menjadi bangunan konseptual yang padu. Di Indonesia dan kawasan Melayu-Nusantara, pengaruhnya terasa dari kampus hingga diskursus kebijakan, dari kurikulum ke publikasi ilmiah, dari ruang kelas ke perbincangan politik nilai (Musa, 2021; Lilly, 2024).
Krisis adab dan loss of adab
Al-Attas sering memulai diagnosa peradaban bukan dari ekonomi, melainkan dari epistemologi: kekacauan pengetahuan melahirkan kekacauan jiwa dan kebijakan. Di sini ia memperkenalkan istilah loss of adab—hilangnya keinsafan tentang “menempatkan sesuatu pada tempatnya”—yang membuat kebingungan konseptual merembes menjadi kebingungan moral (al-Attas, 2001). Adab, dalam pengertian beliau, bukan sopan santun formal, melainkan tatanan batin yang menyadari hierarki realitas: Tuhan, wahyu, akal, indera, dan dunia—serta posisi manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan kebenaran (al-Attas, 2013). Ketika adab runtuh, pengetahuan berubah menjadi sekadar information tanpa orientasi kebenaran dan kebahagiaan (sa‘ādah). Karena itu, pembaruan pendidikan, bagi al-Attas, dimulai dari pemulihan adab—bukan sekadar perbaikan metode atau alat (In’ami, Bambang, & Wekke, 2025).
Kepekaan filosofis ini menemukan dukungan sekaligus kritik membangun dalam riset mutakhir. Di tingkat teori, loss of adab dipandang korelatif dengan “kedaulatan epistemik”—hak suatu tradisi untuk menafsir dunia dari perangkat konsepnya sendiri (Abubakar, 2025). Di tingkat praksis, sejumlah studi pendidikan menegaskan bahwa adab berfungsi sebagai “pembingkai makna” bagi konten sains dan keterampilan abad-21—membuat inovasi tetap berakar pada nilai (In’ami et al., 2025).
Islamisasi Pengetahuan: Membongkar, Menyaring, Merangka
Istilah “Islamisasi pengetahuan” versi al-Attas kerap disalahpahami sebagai “menempelkan label Islami” pada sains modern. Padahal yang beliau maksud jauh lebih halus: mengurai unsur-unsur konseptual Barat (sekularisme, humanisme, dan relativisme) yang “tersembunyi” dalam terminologi kunci; memurnikannya dari assumptions yang bertentangan dengan tauhid; dan merangka kembali konsep dengan kosakata Islam—‘ilm, ma‘rifah, ‘adl, hikmah, nafs, ‘aql—agar koheren dengan worldview Islam (al-Attas, 2001; Musa, 2021). Prosesnya bersifat filologis-falsafati sekaligus historis: bahasa bukan alat netral, ia menyimpan pandangan alam.
Kajian teoretis terbaru mengontraskan model al-Attas dengan pendekatan filsuf kontemporer seperti Taha Abderrahmane, khususnya terkait kritik atas “krisis sains kontemporer” dan netralitas metode (Harvey, 2023). Perbandingan ini menegaskan relevansi al-Attas: kritiknya tidak anti-sains; ia menolak scientism—bukan sains—dan menawarkan fondasi etis-metafisis agar sains kembali answerable kepada kebenaran dan kemaslahatan.
Bahasa, Makna, dan Realitas
Salah satu kontribusi paling khas al-Attas terletak pada relasi bahasa-makna-realitas. Baginya, “makna” adalah “pengenalan tempat dari segala sesuatu dalam suatu sistem”—definisi yang menautkan semantik dengan ontologi (al-Attas, 2001). Karena itu, penyucian istilah adalah kerja peradaban: mengembalikan kata pada “tempat” maknanya. Penelitian mutakhir menyoroti bagaimana al-Attas membangun jembatan antara analisis kebahasaan, intuisi intelektual, dan etika, sehingga pengertian tidak berhenti pada kepala, tetapi menata laku (Ahmadu, 2019). Dari sini, pendidikan Islam (dalam pengertian ta’dīb) tak mungkin netral nilai; ia selalu pembiasaan meletakkan sesuatu pada tempatnya—dari konsep “manusia” (insān) hingga “kebebasan” dan “kebahagiaan”.
Psikologi Insan dan Metafisika Wujūdiyyah
Al-Attas menempatkan manusia sebagai realitas rohani-jasmani yang berjenjang, dengan jiwa (nafs) sebagai pusat kesadaran yang tunduk pada akal dan wahyu—kerangka yang ia rumuskan dalam dialog kreatif dengan tradisi wujūdiyyah (Hamzani, 2024). Pendekatan ini bukan mistik eskapis; ia memberi dasar kuat bagi etika dan politik pendidikan: jika manusia adalah self yang bertingkat, maka kurikulum harus menyesuaikan daya tangkap akliah dan rohaniah peserta didik; jika tujuan akhirnya sa‘ādah, maka evaluasi tidak boleh berhenti pada skor (Fadillah, Kusuma, & al-Lakhm, 2023).
Riset baru di ranah tasawuf falsafi menunjukkan bagaimana al-Attas berdialog dengan Ibn ‘Arabī dalam menafsir tajallī, khayāl, dan dinamika jiwa—sekali lagi, bukan untuk mengulang, melainkan untuk merapikan kategori bagi manusia modern yang tercerai-berai oleh dikotomi lama/baru, rasional/irasional (Ezzat, 2024).
Jejak di Indonesia: Pancasila, Kurikulum, Kebijakan Nilai
Di Indonesia, gagasan al-Attas tidak hadir di ruang hampa. Diskursus tentang Islamisasi dan adab bersentuhan dengan upaya banyak pihak dalam memperkuat fondasi etika pendidikan, bahkan memantik debat tentang relasi agama-negara. Studi terbaru memperlihatkan bagaimana sejumlah intelektual dan gerakan meminjam perangkat al-Attas untuk membaca Pancasila—bukan untuk menggantikan, tetapi untuk memurnikan makna sila-sila dari sekularisasi reduksionis (Lilly, 2024). Temuan ini menarik: al-Attas justru dipakai untuk mengukuhkan keadaban publik—bahwa ruang bersama membutuhkan dasar moral, bukan sekadar prosedur.
Pada saat yang sama, kajian kebijakan menekankan kewaspadaan: Islamisasi pengetahuan mesti diartikulasikan sebagai pengayaan konseptual, bukan instrumentalisasi politik. Karena itu, bahasa “ta’dīb” lebih produktif daripada sloganisasi “label Islami”: ia mendorong integrasi ilmu alam-sosial dengan etika, memperkuat literasi moral tanpa menutup sains dari kritik (Musa, 2021; In’ami et al., 2025).
Relevansi Global: Dari Universitas ke Laboratorium Makna
Apa artinya semua ini bagi universitas hari ini? Pertama, al-Attas menolak dikotomi palsu antara “ilmu agama” dan “ilmu umum”. Keduanya tunduk pada kebenaran yang sama, berbeda pada objek dan method of inquiry, bukan pada nilai (al-Attas, 2013). Kedua, ia mengusulkan curricular core yang memulihkan konsep kunci—manusia, ilmu, keadilan, hikmah—sebelum spesialisasi. Tanpa fondasi ini, spesialisasi menguatkan fragmentasi. Ketiga, ia membela kedaulatan epistemik: tradisi punya hak berbicara dengan bahasanya sendiri, berdialog secara kritis dengan sains modern, dan menyumbang perspektif etik-metafisik untuk krisis global (Abubakar, 2025; Harvey, 2023).
Riset-riset terkini memperlihatkan langkah praktis: pengajaran sains dengan adab (misalnya, memperkenalkan dimensi etis dan konseptual sebelum eksperimen), penataan kurikulum filsafat ilmu berbasis worldview Islam, serta assessment yang mengukur kebajikan intelektual (kejujuran, kehati-hatian, kerendahan hati epistemik)—bukan hanya keterampilan teknis (In’ami et al., 2025; Fadillah et al., 2023).
Menimbang Kritik, Merawat Warisan
Tentu, tidak semua sepakat. Kritik menyasar “abstraksi berlebihan” dan “generalisasi” tentang Barat. Di sini, dialog dengan pemikir kontemporer membantu: perbandingan dengan Abderrahmane, misalnya, menunjukkan perlunya memperjelas jembatan antara metafisika dan institusi—dari prinsip ke kebijakan (Harvey, 2023). Namun kritik ini justru memperkaya: ia memaksa pembaca al-Attas untuk memperinci how-to tanpa melepaskan why. Sementara itu, kajian bahasa dan sejarah memperkuat fondasi metodologis al-Attas—bahwa pemurnian istilah adalah kerja ilmiah, bukan ideologis (Ahmadu, 2019).
Warisan al-Attas juga dirawat melalui karya suntingan dan telaah generasi penerus—mendokumentasikan sistem filsafatnya, memperbarui dialog dengan ilmu-ilmu kontemporer, dan menyiapkan perangkat ajar yang operasional (Wan Daud, 2022). Di ranah tasawuf, riset baru merapikan korespondensi konsep jiwa, akal, dan wujūd dalam kerangka al-Attas sehingga dapat menjawab problem mind-body modern (Hamzani, 2024). Semua ini menunjukkan bahwa al-Attas bukan sosok monumen; ia tradisi intelektual yang hidup.
Penutup: Menjaga rumah makna
Pada akhirnya, sumbangan terbesar al-Attas adalah mengingatkan kita bahwa universitas adalah rumah makna sebelum laboratorium teknologi; bahwa krisis modernitas bukan pertama-tama krisis alat, tetapi krisis penataan makna. Jalan keluarnya bukan anti-sains, melainkan sains yang beradab; bukan isolasi, melainkan dialog kritis yang percaya diri; bukan menutup diri dari kemajuan, melainkan memandu kemajuan dengan kompas metafisika yang jernih.
Menghidupkan kembali adab, memurnikan konsep, dan merangka kurikulum yang setia pada tauhid adalah tugas panjang. Tetapi sebagaimana diingatkan al-Attas, tugas intelektual pada akhirnya adalah tugas moral—menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di tengah hiruk-pikuk zaman, itulah pekerjaan paling mendesak universitas, pendidik, dan warga—agar ilmu kembali menjadi jalan pulang kepada kebenaran (al-Attas, 2001; 2013).
Referensi
- Abubakar, S. D. (2025). Islam and the challenge of epistemic sovereignty: An overview of paradigm and decolonial imagination of knowledge in Islam. Religions, 15(4), 406. Basel: MDPI. https://doi.org/10.3390/rel15040406
- Ahmadu, S. I. (2019). Al-Attas on language and thought: A contribution toward Islamization of contemporary knowledge. TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 12, 121–138. Kuala Lumpur: IKIM.
- al-Attas, S. M. N. (2001). Prolegomena to the metaphysics of Islam (2nd ed.). Kuala Lumpur: ISTAC.
- al-Attas, S. M. N. (2013). Islam: The concept of religion and the foundation of morality. Kuala Lumpur: IBFIM.
- al-Attas, S. M. N. (2023). Islam: The covenants fulfilled. Kuala Lumpur: Ta’dib International.
- Arrozy, J. (2025). Al-Attas, Husserl, and critique of technocratic knowledge: A prolegomena to the Islamic metaphysics of nature. TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 18(1), 69–89. Kuala Lumpur: IKIM. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol18no1.3
- Ezzat, A. H. (2024). Between two Sufis: Reason, imagination and the soul in Ibn ‘Arabī and S. M. N. al-Attas. In A. H. Ezzat, S. Vesely, & F. Vanzago (Eds.), Imagining soul. On reason, imagination, and the soul in Islamic thought (pp. 205–224). Venice: Fondazione Giorgio Cini.
- Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & al-Lakhm, N. R. R. (2023). The concept of science in Islamic tradition: Analytical studies of Syed Naquib al-Attas. Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 7(1). Ponorogo: UNIDA Gontor.
- Hamzani, D. N. (2024). The soul-body relation from the perspective of the wujūdiyyah Ṣūfī metaphysics with a special focus on Syed Muhammad Naquib al-Attas’s metaphysical framework. TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 17(2), 57–84. Kuala Lumpur: IKIM. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol17no2.3
- Harvey, R. (2023). Islamic theology and the crisis of contemporary science: Naquib al-Attas and Taha Abderrahmane. Theology and Science. Abingdon: Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/14746700.2023.2256041
- In’ami, M., Bambang, & Wekke, I. S. (2025). Contextualising adab in Islamic education from the perspective of al-Attas. Journal of Al-Tamaddun, 20(1), 145–158. Kuala Lumpur: University of Malaya.
- Lilly, P. (2024). Al-Attas, Islamization and Pancasila: The impact of Attasian thought on political Islam in Indonesia. Muslim Politics Review, 3(1), 84–116. Depok: UIII Press.
- Musa, M. F. (2021). Naquib al-Attas’ Islamization of knowledge (Trends in Southeast Asia No. TRS16/21). Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Wan Daud, W. M. N. (Ed.). (2022). Syed Muhammad Naquib al-Attas: His philosophical system and conceptions of humanity, history and civilization. Kuala Lumpur: RZS-CASIS & HAKIM.
- Zainiy Uthman, M. (2022). Al-Attas’ psychology: The soul of man and the human spirit. Kuala Lumpur: HAKIM.