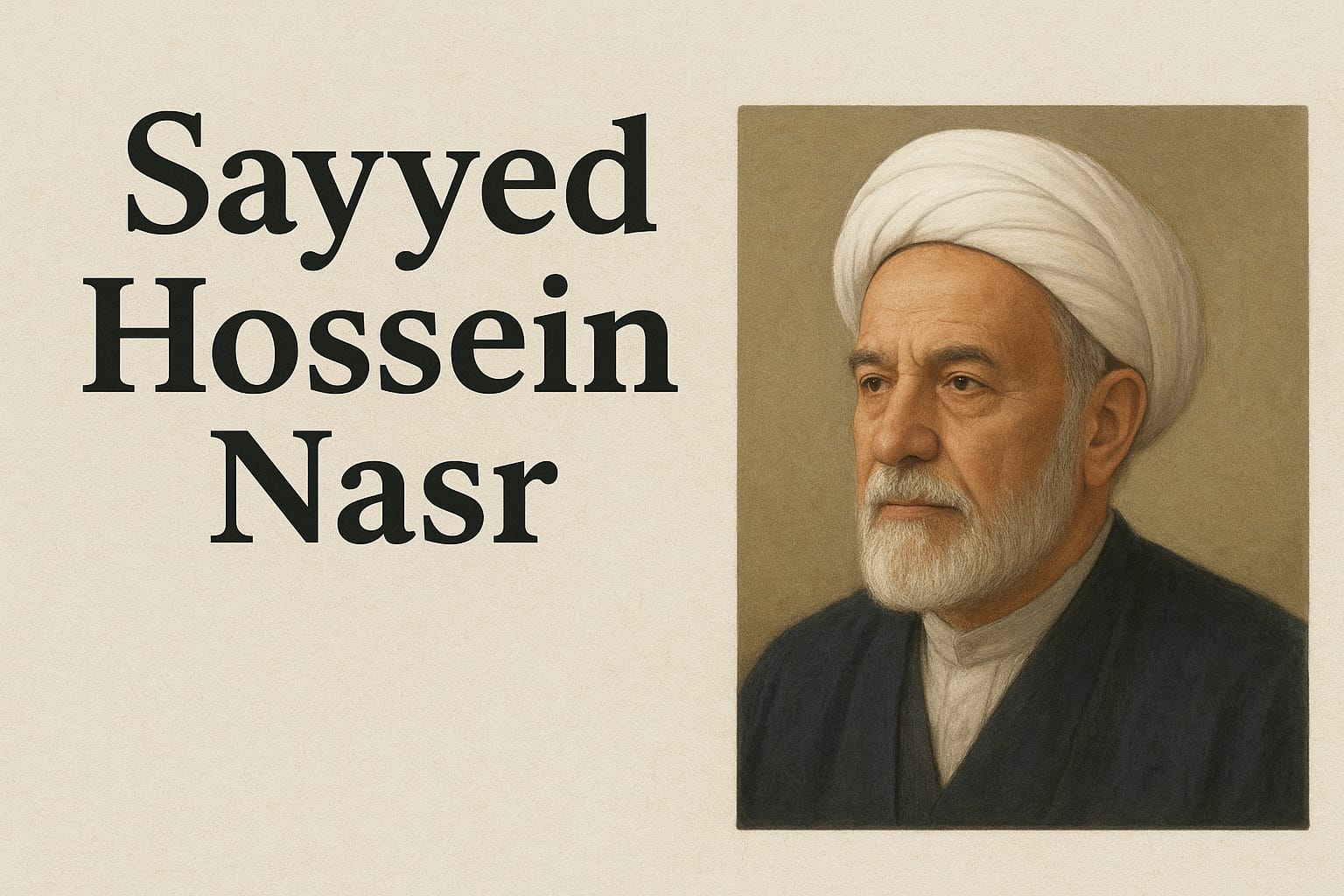Dr. H. Tirtayasa, S.Ag., M.A.
Kader Seribu Ulama Doktor
MUI dan Baznas RI Pusat Angkatan 2021
Di saat wacana publik modern sering bergolak oleh dualisme kemajuan versus tradisi, wacana intelektual Seyyed Hossein Nasr hadir sebagai pengingat bahwa problem kita bukan sekadar kecepatan teknologi atau akumulasi pengetahuan, melainkan desakrasi pengetahuan itu sendiri. Nasr, seorang sarjana Islam yang menulis dan berbicara lintas disiplin—dari filsafat, sufisme, sejarah ilmu, hingga ekologisme—mengajukan klaim sederhana namun radikal: ilmu pengetahuan modern, dalam bentuknya yang dominan, gagal menyediakan makna dan tujuan; ia mengikis dimensi sakral yang mengikat manusia dengan kosmos (Nasr, 1989; Nasr, 1993).
Pernyataan semacam ini mungkin terdengar konservatif, bahkan romantik terhadap masa lalu. Namun bagi Nasr bukan soal nostalgia. Ia menghendaki rehabilitasi epistemologis: ilmu yang mengenali tingkatan realitas dan relasi antara lahir dan batin—yang ia sebut scientia sacra—sebagai kompas etika dan metafisika bagi peradaban kontemporer (Nasr, 1989). Tanpa kompas ini, teknologi dan metode ilmiah tetap berfungsi, namun kehilangan arah: kemampuan untuk menjawab “mengapa” yang mendasari “bagaimana” (Nasr, 1993).
Apa implikasi klaim ini bagi pembaca awam? Pertama, Nasr menegaskan bahwa modernitas memisahkan manusia dari dimensi sakral lingkungan—akibatnya muncul krisis lingkungan yang bukan hanya teknis melainkan spiritual (Nasr, 1991). Pandangan ini merangkum kritik yang kini menjadi arus utama: kerusakan alam tidak cukup dijelaskan oleh kegagalan kebijakan atau pasar; terdapat pula disfungsi konsep manusia dan alam yang dibentuk paradigmatis oleh ilmu modern (Nasr, 1991). Dalam ranah kebijakan publik, pendekatan semacam ini dapat merangsang kebijakan lingkungan yang memperhitungkan nilai-nilai kultural, religius, dan estetis—bukan hanya cost–benefit teknis semata.
Kedua, Nasr menempatkan tradisi bukan sebagai “museum” ajaran lampau tetapi sebagai reservoir pengetahuan hidup: simbol, ritual, etika, dan praktik spiritual yang membentuk cara manusia memahami dunia dan dirinya (Nasr, 1989). Dalam wacana publik Indonesia yang plural, gagasan ini relevan karena membuka ruang dialog antara ilmu modern dan kebijaksanaan tradisional lokal—dari kearifan ekologi masyarakat pesisir sampai ritual-ritual komunitas agraris—yang selama ini sering direduksi menjadi “budaya” tanpa bobot epistemik. Nasr memberi legitimasi intelektual bagi upaya merevitalisasi kebijaksanaan lokal sebagai sumber solusi kontemporer (Chittick, 2007).
Namun, kritik terhadap Nasr juga perlu didengarkan. Beberapa sarjana menilai tuntutan kembali ke scientia sacra berisiko romantisasi tradisi yang mengaburkan konteks historis ketidakadilan yang juga diwariskan tradisi itu sendiri. Nasr menyadari hal ini: ia bukan mendukung konservatisme sosial sebarang, melainkan menegaskan aspek transformatif tradisi—yang bisa mengoreksi kelalaian modernitas—tanpa memaksakan bentuk historis tertentu (Nasr, 1993). Dialog kritis semacam ini penting: kita perlu memilah antara inti metafisik yang menawarkan makna, dan praktik-praktik sosial historis yang patut dipertanyakan atau diubah.
Kekuatan karya Nasr terletak pada jangkauan lintas-kulturalnya. Ia menunjukkan bahwa simbol-simbol metafisik besar—dari sufisme Islam sampai tradisi Vedanta atau mistisisme Kristen—mengandung bahasa serupa tentang hubungan manusia-dengan-Transenden (Nasr, 2007). Pendekatan ini membuka ruang dialog antaragama yang didasarkan pada kedalaman spiritual, bukan sekadar retorika pluralisme formal. Dalam konteks Indonesia yang beragam, arsitektur dialog semacam ini bisa membantu menahan politisasi agama yang meruncing—dengan syarat dialog itu sungguh-sungguh mengingat aspek batiniah tradisi, bukan hanya seremonialnya.
Di dunia akademik, Nasr juga mencampakkan sikap mudah terhadap sekularisasi ilmu: ia menuntut akuntabilitas akademik yang mampu merefleksikan nilai-nilai transenden, bukan semata kuantifikasi. Ini bukan seruan untuk meniadakan ilmu modern, melainkan mendorong ilmu itu memasukkan parameter makna—misalnya, ketika menilai teknologi baru, pertanyaan etis dan eksistensial harus menjadi bagian integral, bukan sekadar eksternal (Nasr, 1989; Nasr, 1993). Bagi pembuat kebijakan pendidikan, wacana ini mengusulkan kurikulum yang membekali mahasiswa tidak hanya kompetensi teknis tetapi juga dimensi etika, estetika, dan spiritual.
Sebagai catatan, pembaca mungkin menanyakan relevansi pemikiran Nasr di era post-truth dan AI: bukankah instrumentasi modern semakin tak terelakkan? Jawabannya: relevansi Nasr justru pada kemampuan mempertanyakan arah tujuan instrumentasi itu. Nasr tidak menolak kecanggihan teknis; ia mempertanyakan kecenderungan teknologi yang mengejar efisiensi tanpa mempertimbangkan kebijaksanaan. Dalam soal AI dan otomasi, perspektifnya mendorong diskursus tentang martabat manusia, tanggung jawab kolektif, dan batas-batas penggunaan teknologi—bukan menolak inovasi tetapi menuntut kebijaksanaan penerapan.
Akhirnya, warisan intelektual Nasr adalah undangan: bukan kembali ke masa lalu ‘seutuhnya’, tetapi menghidupkan kembali dimensi batin yang memberi makna. Di tengah kebisingan berita dan ritme modern yang memecah perhatian kolektif, gagasan Nasr mengajak kita menahan sejenak, menegakkan kembali perspektif makro tentang tujuan hidup dan relasi manusia-alam. Untuk republik gagasan seperti Indonesia, itu bukan kemewahan—melainkan kebutuhan: agar pembangunan tidak mengerucut menjadi urusan teknik belaka, tapi kembali menjadi upaya membangun manusia utuh yang berakar pada etika, spiritualitas, dan tanggung jawab ekologis (Nasr, 1991; Nasr, 1993).
Dalam praktiknya, menerjemahkan pemikiran Nasr ke ranah kebijakan berarti memasukkan narasi nilai dalam perencanaan lingkungan, pendidikan yang menyeimbangkan kecerdasan kognitif dan spiritual, serta kebijakan teknologi yang menguji dampak etis selain efek ekonomi. Bukan tugas satu kelompok—melainkan pekerjaan kolektif lintas sektor: akademisi, agamawan, pembuat kebijakan, dan warga biasa. Bila Nasr mengingatkan bahwa ilmu tanpa sakralitas rentan kehilangan arah, pesan itu mesti kita dengarkan sebagai seruan untuk menata kembali prioritas: ilmu untuk kehidupan, bukan hanya ilmu untuk produksi.
Referensi
- Chittick, W. C. (Ed.). (2007). The essential Seyyed Hossein Nasr. Bloomington, IN: World Wisdom.
- Lumbard, J. E. B. (2013). Introduction. In W. C. Chittick (Ed.), The essential Seyyed Hossein Nasr (pp. ix–xiii). Bloomington, IN: World Wisdom.
- Nasr, S. H. (1989). Knowledge and the sacred. Albany, NY: State University of New York Press.
- Nasr, S. H. (1991). Man and nature: The spiritual crisis of modern man. Chicago, IL: ABC International Group.
- Nasr, S. H. (1993). The need for a sacred science. Albany, NY: State University of New York Press.
- Nasr, S. H. (2007). The garden of truth: The vision and promise of Sufism, Islam’s mystical tradition. New York, NY: HarperOne.
- Nasr, S. H., Dagli, C. K., Dakake, M. M., Lumbard, J. E. B., & Rustom, M. (Eds.). (2015). The study Quran: A new translation and commentary. New York, NY: HarperOne.
- Nasr, S. H. (2006). Islam, science, Muslims, and technology: Seyyed Hossein Nasr in conversation with Muzaffar Iqbal. Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Book Trust.
- Nasr, S. H. (2002). Islam: Religion, history, and civilization. San Francisco, CA: HarperSanFrancisco.
- Nasr, S. H. (1996). Religion and the order of nature. New York, NY: Oxford University Press.
- Nasr, S. H. (1996). Traditional Islam in the modern world. London, England: Kegan Paul International.
- Nasr, S. H. (2003). The heart of Islam: Enduring values for humanity. New York, NY: HarperOne.
- Nasr, S. H. (1999). Islamic art and spirituality. Albany, NY: State University of New York Press.
- Nasr, S. H., & Leaman, O. (Eds.). (1996). History of Islamic philosophy. London, England: Routledge.
- Seyyed Hossein Nasr — Official Website. (n.d.). Retrieved from https://www.seyyedhosseinnasr.com